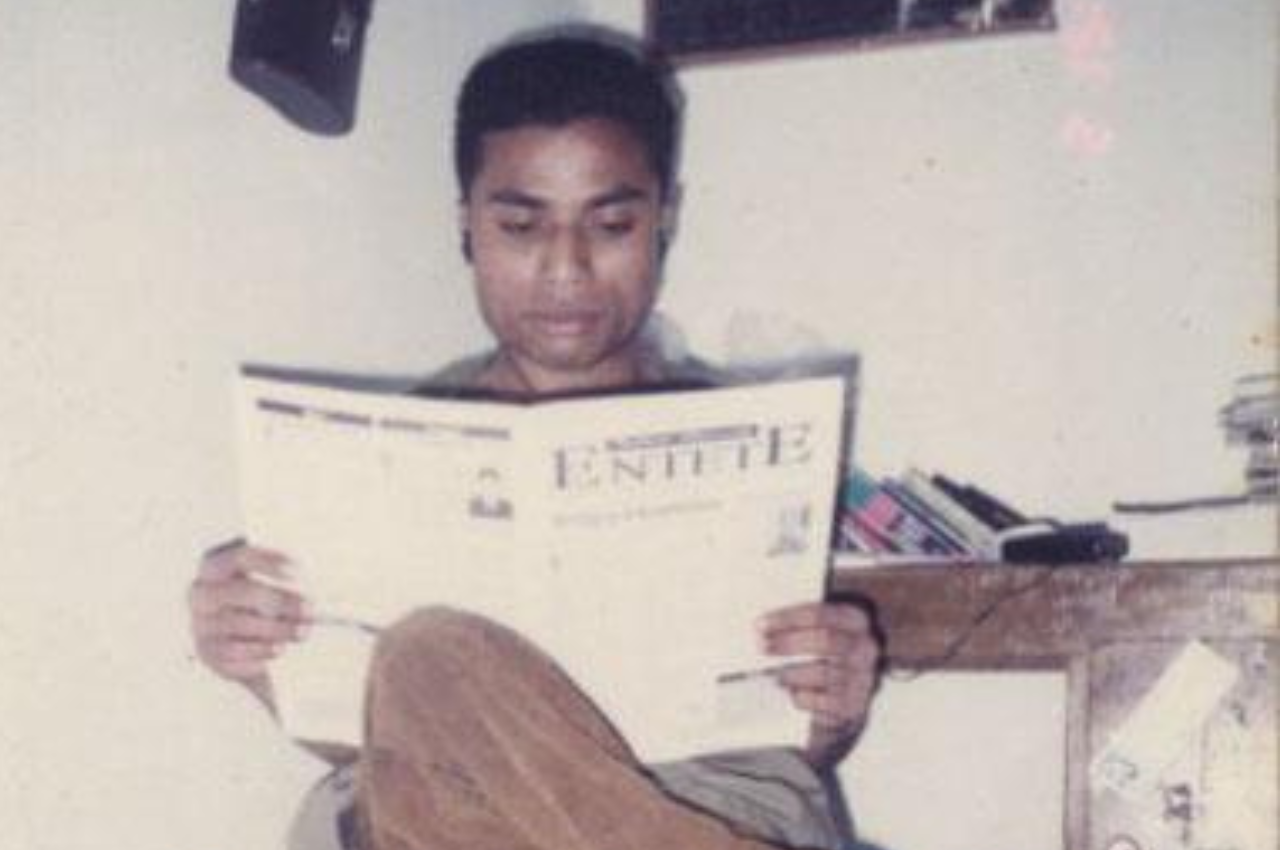gbm.my.id – Kita mengharapkan kebenaran Tragedi Cebongan terungkap. Namun, beragam tanggapan masyarakat—dari akar rumput, kelas menengah, hingga pejabat—menunjukkan ambiguitas sikap terhadap tragedi kemanusiaan ini. Kita belum memiliki keseragaman pemahaman dalam MENGUTUK APAPUN BENTUK KEJAHATAN KEMANUSIAAN, seperti pembunuhan, tanpa melihat alasan ataupun siapa pelakunya.
Menulis di Tengah Gejolak
Ketika tragedi Cebongan membuncah, saya menulis refleksi berjudul Kembali ke Fitrah Tujuanmu: Kuliah. Sebuah otokritik yang lahir di tengah situasi yang memanas. Saat menulis, batin saya berkecamuk menghadapi potensi pro dan kontra. Namun, saya memilih tetap menulis dengan prinsip yang teguh. Dugaan saya bahwa akan ada resistensi, ternyata meleset. Seratus persen tanggapan terhadap tulisan itu justru positif.
Charles Conrad Rambung, alumnus Sanata Dharma Yogyakarta yang kini menempuh studi magister di UNSW Sydney, mengirim pesan pribadi kepada saya:
“Anda menulis dengan baik bagaimana kita harus merespons tragedi ini agar tidak terjebak dalam kebencian dan isu SARA. Ini yang membuat tulisan Anda berbeda. Anda tidak hanya memperkarakan siapa yang jahat atau seberapa buruk sisi HAM dalam tragedi ini, tetapi Anda menghadirkan pendekatan baru—pencerahan dan kesadaran baru.”
Tulisan saya bukanlah untuk menelanjangi diri atau para alumnus Yogyakarta lainnya, melainkan sebuah upaya berbagi pengalaman dengan mahasiswa asal NTT. Saya ingin mengingatkan mereka agar tidak terseret dalam tragedi berdarah seperti yang terjadi di Hugo’s Cafe dan Lapas Cebongan.
Disorientasi Mahasiswa Perantauan
Peristiwa ini berpangkal dari disorientasi tujuan di kalangan mahasiswa asal NTT. Novita Herewila, alumnus Universitas Atma Jaya, menegaskan:
“Motivasi awal setiap anak merantau untuk kuliah adalah menuntut ilmu. Namun, motivasi itu bisa berubah jika tidak memiliki karakter yang kuat. Pergaulan bisa merusak kebiasaan baik.”
Novi, sapaan akrabnya, juga menekankan bahwa ia menolak pelanggaran HAM. Setiap warga negara berhak atas hukum yang adil, dan negara bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi di tangan aparatnya.
Elias Sumardi Dabur, alumnus Sastra Prancis UGM dan kader muda Partai Amanat Nasional, turut mengungkapkan pandangannya:
“Sepenuhnya setuju. Kita harus mengutuk dan mendesak aparat hukum untuk menuntaskan kasus ini serta menghukum para pelaku.”
Sebaliknya, Bung Ely melihat tragedi ini sebagai momentum bagi mahasiswa NTT di Yogyakarta untuk kembali kepada fitrah mereka sebagai pencari ilmu.
Antonius Nugraha Widhi Pratama, dosen Universitas Jember dan mahasiswa magister di Perth, mengungkapkan kesedihannya:
“Mungkin ada latar belakang politik di baliknya, tetapi ini keji. Tidak fair mengambil nyawa orang seenaknya sendiri.”
Sementara itu, Eddy Due Woi, alumnus STMIK AKAKOM dan PNS Pemda Nagekeo, menyoroti ketidakprofesionalan dalam menyikapi tragedi ini:
“Ternyata bukan hanya dunia premanisme yang tidak profesional. Ternyata bukan hanya masyarakat yang suka main hakim sendiri.”
Tragedi dan Ambiguitas Rakyat
Tragedi Cebongan menelanjangi wajah buram HAM di negeri ini dan menunjukkan betapa mudahnya aparat mengambil nyawa orang tanpa kemanusiaan, bahkan di dalam institusi hukum. Peristiwa ini pun mengundang berbagai reaksi dari masyarakat. Ketika tersiar bahwa oknum militer terlibat, harapan akan penyelesaian yang tuntas semakin redup. Prasangka dan teori konspirasi bermunculan, sementara pemutarbalikan fakta mengancam proses hukum.
Ironisnya, sebagian masyarakat justru mendukung aksi ini. Banyak opini yang mengidentifikasi korban sebagai “preman” dan menyebut tindakan para pembunuh sebagai “kesatria”. Tragedi ini pun menjadi bola liar yang bergulir tanpa arah yang jelas.
Dua peristiwa—Hugo’s Cafe dan Lapas Cebongan—adalah luka besar bagi nilai-nilai kemanusiaan. Namun, ambiguitas sikap rakyat Indonesia kembali terlihat. Di satu sisi, masyarakat menolak pembunuhan di Hugo’s Cafe, tetapi di sisi lain, mereka mendukung eksekusi di Lapas Cebongan. Apakah kejahatan harus selalu dibalas dengan kejahatan?
Tragedi ini mencerminkan prinsip “darah dibalas darah, gigi ganti gigi”—sebuah pola barbarisme yang menyayat hati. Seharusnya, nilai kemanusiaan melampaui sekat-sekat suku, agama, dan golongan.
Refleksi: Bangsa yang Terfragmentasi
Tragedi Cebongan memperlihatkan bagaimana masyarakat kita mudah terfragmentasi oleh latar belakang budaya dan identitas kelompok. Demonstrasi yang mendukung para pelaku di Yogyakarta menjadi bukti betapa nilai kemanusiaan kita semakin kabur.
Seharusnya, solidaritas kemanusiaan tidak bersyarat. Nilai kemanusiaan itu universal—tidak boleh terikat oleh suku, golongan, atau agama. Namun, realitas menunjukkan sebaliknya. Kepentingan dan perbedaan latar belakang telah menyempitkan cara kita memahami tragedi.
Kini, refleksi bagi kita semua: dapatkah kita bersikap netral dan adil terhadap tragedi kemanusiaan tanpa terpengaruh identitas korban atau pelaku? Bisakah kita menegakkan nilai-nilai kemanusiaan tanpa terjebak dalam bias primordial?
Harapan terakhir tertumpu pada para penegak hukum. Semoga tragedi ini dibedah dengan dalil-dalil hukum yang berlandaskan kemanusiaan, sehingga keadilan dapat ditegakkan bagi semua pihak.
(gbm)